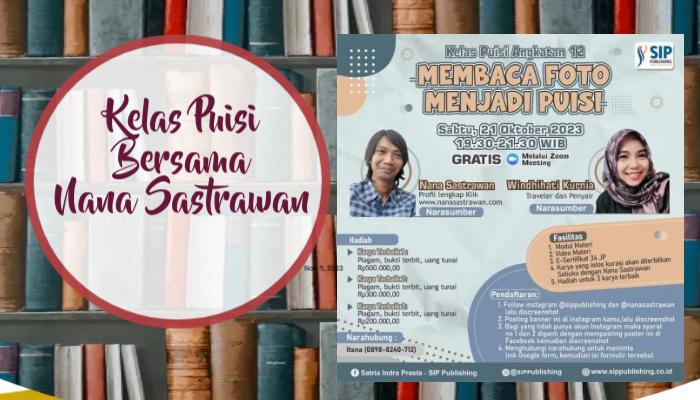Oleh Nana Sastrawan[1]
Menulis puisi bisa dilakukan dengan berbagai cara satu di antaranya melalui foto. Ketika inspirasi macet, tak ada ide untuk memulai menulis, foto sebagai jembatan memancing ingatan pada peristiwa-peristiwa. Foto juga dapat dihadirkan dalam proses menulis puisi sebagai obyek untuk menuliskan kata pertama; misalkan kita melihat laut dalam foto tersebut. Kita bisa menuliskan kata ’laut’ pada awal menulis puisi, dan selanjutnya dapat meneruskan kalimat-kalimat lainnya ketika pikiran atau imajinasi kita mulai bekerja.
Dalam buku ini, terkumpul ratusan puisi yang tercipta melalui foto-foto dari para penulisnya, dan dapat dibaca sebagai puisi yang utuh dalam karya sastra tanpa harus disandingkan dengan foto yang sejak awal memengaruhi proses menulisnya. Sebagai pembaca, ketika membaca puisi-puisi dalam buku ini, tanpa disadari bahwa puisi-puisi dalam buku ini ditulis dengan melihat foto. Itulah kekuatan puisi. Ia akan menjadi makhluk kreatif dan imajinatif penulisnya, berdiri sendiri dengan makna yang luas dan dalam. Sehigga, foto yang sejak awal memantik penulis untuk memulai menulis puisi, tak perlu lagi disandingkan dengan puisinya dalam buku ini. Biarlah pembaca memaknai puisi-puisi dalam buku ini secara merdeka tanpa terganggu dengan foto yang berseliweran di setiap halamannya.
Ada tiga puisi yang menarik perhatiannya dari ratusan puisi tersebut. Bagaimana teks puisi tersebut hadir dan terasa kuat dalam pemilihan diksi, gaya bahasa, tipografi dan lain-lain dan melepaskan diri bayang-bayang foto yang sejak awal dihadirkan sebagai pemantik dalam proses menulisnya. Sebab, teks puisi dan foto memang memiliki keilmuan yang berbeda sekaligus kemiripan; foto sebagai cabang seni rupa melalui cahaya, sedangkan puisi memiliki keindahan rupa dengan setiap teks yang tersusun.
Berikut ketiga puisi tersebut yan juga memiliki kekuatan makna yan berbeda; puisi ’Kabut’ dapat kita masuki ruang kehangatan antara hubungan alam, manusia dan penciptanya. Puisi yang memiliki nilai-nilai religius. Sedangkan puisi ’dari Kota Papan Ke Harum Emas Lumpur Asmat’ mempunyai nilai-nilai sosial, budaya, politik dengan menghadirkan ilustrasi ‘asmat’ di pulau papua. Hampir memiliki kemiripan dengan puisi ‘Ibu, Rindu, dan Anak Luka’. Namun pada puisi ini nilai-nilai kemanusiaan begitu dominan, dengan tema cerita ’Malin Kundang’ dari tanah Minang.
Wayan Esa Bhaskara
KABUT
tersamar engkau
di antara kabut, pagi itu
pepohonan, dedaunan basah
di sela-sela rindu
dan gelisah jarak waktu
yang ditanam pada hati
paling dalam
gigil sepasang tubuh
akan muara cerita
yang mengalir dari
mata jujur, dan kata-kata kanak-kanakmu
ratusan burung bernyanyi
kita terdiam saja—seperti risau
aku masih memelukmu
merasa hangat bibirmu
sambil kubaca
baris-baris puisi dalam tubuhmu
Badung, 2023
Budi Saputra
DARI KOTA PAPAN KE HARUM EMAS LUMPUR ASMAT
Dari bentangan papan kepungan rawa, selain mengenal
magis pohon sagu dan seni ukir Fumiripitsy, aku mengenal
wangimu yang tersimpan di kedalaman lumpur.
Dari deret perempuan penjual ikan dan sayur, dari
toko-toko kelontong pendatang yang menyajikan
beras dan kopi, serta dari patung Jan Smith seakan
kekal di dermaga, aku melintasi punggung
Sungai Sirets dan mengendus gubal yang seperti
buah dada hutan yang ranum.
Sebagai titisan dewa dengan segala keberkahan
semesta, kupahami hidup yang begitu dekat
dengan Yi-ow.
Hidup berjalan semestinya di dinding sederhana
sekolah dalam belajar aksara, mufakat jew,
atau rumah penampung air hujan dialiri tropis
kalender air membaca segala tabiat
dan siasat sungai.
Sebab bivak-bivak mesti bermekaran dalam
keteduhan hutan. Kujelang pagi dengan butir
doa dalam tarian langit kirmizi.
Kutebus jerih payah mama memangkur dengan
noken terisi penuh di kepala, hingga yang terbayang
hanyalah kesunyian kampung dan nyanyian
burung-burung belaka.
Tanpa tulang kasuari, kuceburkan diri ke dalam
kubangan hingga menemukan dirimu yang menjadi
bagian jalan terang pemujaan roh leluhur melalui
ukiran kayu besi. Harga-harga pun melambung,
hingga malam-malam merayap penuh arti ketika
orang-orang menyantap sagu dan karaka
dan melupakan campak, kolera, dan muntaber
merenggut puluhan nyawa anak
pada 1960-an di Kapi.
Dari bentangan papan kepungan rawa, selain mengenal
magis pohon sagu dan seni ukir Fumiripitsy, aku mengenal
wangimu yang tersimpan di kedalaman lumpur.
Dari derasnya arus zaman di Asmat, dari kabut hitam
gizi buruk yang bergentayangan seperti hantu,
aku ingin dirimu tak punah-punah dan terus mengakar
dalam kobar matahari dan sehamparan lembayung
petang.
Lembayung petang yang penuh harapan,
seiring dayung perahu lesung yang pulang ke tepian
dalam bahasa kebahagiaan.
2023
Faidi Rizal Alief
IBU, RINDU, DAN ANAK LUKA
dada seorang ibu tak selalu telaga, Anakku Malin,
ini yang hari ini kamu lupa atau hanya pura-pura
saja? Sehingga kamu datang dengan perahu
besar, berlabuh di pesisir yang seluruh lautnya masih
berdasar cintaku, berombak doaku, dan berkarang kesalku
sebenarnya sudah aku siapkan bunga-bunga
yang dibesarkan air mata dan rindu, Anakku
saat ombak mengabarkan kepulanganmu,
saat laut melihatmu tak lagi bujang
tapi rupanya yang datang ke hadapanku hanyalah
luka menyamar jadi paras perih yang merias wajah istrimu
dengan sengaja mempermainkan segenap
cemasku yang rentan pecah
sial sekali hari ini, Malin, mata rinduku tak melihat
malu yang menjalar dari urat-urat lehermu, bergemuruh
di sepanjang aliran darahmu, dan benar-benar melepuh
di kedua matamu yang seluruhnya mendidih
sungguh! Sial sekali, Malin. Laut dan seluruh gelombangnya
tak memberitahuku, bahwa sudah tak ada ibu di perahu
dadamu. Tak ada ibu di kedua mata cantik istrimu.
yang kamu angkut dan kamu bawa seluruhnya hanyalah
perempuan cantik yang tak pernah tahu bagaimana
perihnya mengandung, melahirkan, dan membesarkan
seorang anak, yang tak pernah paham betapa masa lalu
masih jauh lebih berkilau dari manik-manik kalungnya dari
silau pakaiannya dari segala yang diberikannya padamu
dan aku peluk saja tubuhmu yang kusangka masih Malin yang dulu,
aku raih tangan istrimu dan sungguh! Nyaris aku cium seluruh
dirimu dirinya dengan sisa masa lalu yang kusimpan
tapi lebih dulu seluruh tubuhku dijamah duri dan berdarah
karang-karang di hati yang dikuatkan kenangan retak
oleh dirimu dirinya yang menepis segalaku
laut mendadak merah melihat ketidakberdayaanku,
ombak-ombaknya mengeras
dari kekecewaanku, anginnya mendekat dari
rasa maluku, tapi, Malin, aku masih bertahan dan menahannya
sebagai seorang ibu yang benar-benar seorang ibu
bagi seluruh dirimu meski sebagian tubuhku sudah kaku
dan diam-diam perih paling sunyi yang terus
menjalar dari dasar laut di belakangmu,
melewati karang-karang dan lidah ombak
masih bisa kukembalikan ke seberang doaku
aku genggam tanganmu sekali lagi, kaupatahkan tulang dadaku,
aku pegang kakimu sekali lagi, kautendang kesabaranku
aku jelaskan seluruh kisah kecilmu padanya
ia meremas dan melemparkannya ke mukaku
hingga seluruh diriku tersungkur dan terbentur perih
kehampaan menarik tanganku yang terluka, kekosongan
menopang tubuhku yang terluka, kegelapan membangkitkan
hatiku yang terluka, tapi matamu pura-pura buta,
pura-pura tak melihat kejanggalan laut di belakangmu
padahal di dasarnya sudah bergemuruh prahara besar
yang akal sehatmu tak akan mampu menaksirnya
sebab masa lalu itu juga benar-benar padam di dadaku
tanganmu sendiri yang mengubah air mataku jadi api, Malin
hingga mengeras seluruh tulang sumsummu, kulitmu,
dagingmu, kukumu, rambutmu
kata-katamu sendiri yang melempar doaku ke dasar paling
kelam, Malin hingga luka seluruh ibu di bumi ini menamparmu
dan mengembalikanmu pada tanah paling muram
rasa malumu sendiri yang berlebihan, Malin yang
menyerahkan tanganku ke langit
hingga seluruh batu menutup dirimu
dan sebagai ibu yang kehilangan seluruh hidupnya, aku
pasrah dikutuk sejarah sebagai penyesalan yang
diam-diam masih menunggu waktu
meretakkan batu di hadapan tangisku sendiri
Bandungan, 2023
[1] Peraih penghargaan Acarya Sastra IV dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 2015