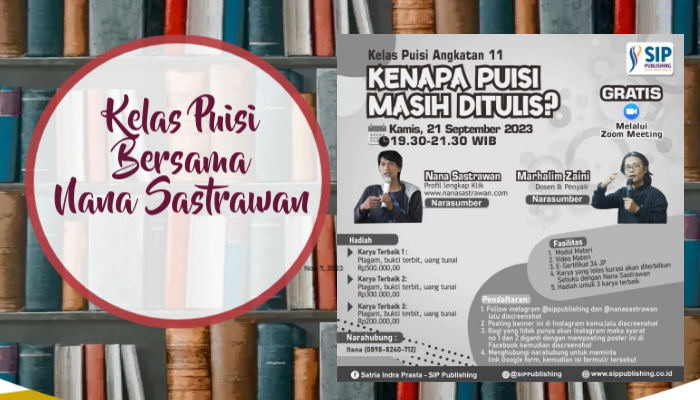Oleh Nana Sastrawan[1]
Mengira seorang kurator puisi dapat memberikan kemudahan untuk pemilihan puisi-puisi yang akan ditayangkan di media online, apalagi media itu berhonor, seorang penulis datang pada saya: Kang Nana, minggu depan puisi saya bisa dimuat?
Sejenak saya terdiam, sambil memandang wajahnya. Tentu saja tampak dari raut wajahnya, ia serius mengatakan itu.
“Saya tak bisa.”
“Loh, kenapa Kang? Saya sudah sering menerbitkan buku loh.”
“Bagaimana mungkin saya bisa memuat puisi yang belum pernah saya baca. Jika ingin mengirim, boleh-boleh saja.”
Setelah peristiwa itu, ia tidak pernah bertegur sapa lagi. Bahkan kerap kali ia mengkritik saya dalam urusan tulis menulis. Secara sadar, dampak itu akan terjadi pada diri saya, apalagi dunia sastra sudah dikenal keras, kejam dan memiliki sensitivitas tinggi pada perasaan. Tapi itulah kenyataannya, saya tak bisa memberikan penilaian pada sebuah karya tanpa membacanya.
Untuk kuat seorang penulis butuh tempaan, dalam hidupnya dan pada karya-karyanya. Saya sepakat. Namun, saya tidak ingin mewarisi sikap keras dan kejam dari para penulis-penulis atau penyair-pernyair terdahulu. Saya ingin membawa teks sastra pada kegembiraan di dalam prosesnya, untuk itulah kelas-kelas menulis sering saya ciptakan sekaligus membukukan karya-karya mereka meskipun masih tergolong mentah. Dalam belajar menulis puisi, mereka butuh ruang, butuh orang-orang membacanya agar karya-karya mereka terus hadir, dan menjadikan terlatih untuk menulis, membaca, berdikusi hingga mereka dapat mencapai tingkatannya sesuai dengan batas kecerdasan mereka dalam berbahasa.
Eksistensi kepenyairan sebenarnya ada pada ‘menulis puisi’ bukan mengejar-mengejar kurator atau redaktur, dan seorang penyair harus yakin dengan kepenyairannya. Sebab tantangan penyair ialah dirinya sendiri. Ia harus melatih kepekaan batinnya, menangkap makna kehidupan. Untuk itulah, saya menganjurkan penyair harus bertahan hidup, terluka, ketawa-ketiwi, lapar, kenyang, setengah gila, bila perlu teriak-teriak dalam gelap.
Bicara soal melatih kepekaan dalam menangkap makna kehidupan, dari buku ini, saya menemukan banyak puisi-puisi yang senafas secara tema, dan rata-rata tidak terlalu padat bermain dengan diksi, majas, citraan, bunyi dll. Sehingga ‘kegembiraan’ dapat ikut saya rasakan pula dengan membacanya di atas pohon, sambil berayun-ayun merasakan angin kemarau.
Dari puisi-puisi itu ada tiga yang menarik perhatian saya. Yang pertama puisi berjudul ‘Layang-Layang di Langit Musim Kemarau’ karya Waghfirotul Qona’ah dari Bangkalan.
Tidak ada lagi malam sunyi
Saat surya terlelap di musim kemarau
Hiruk-pikuk kesibukan mulai menyepi
Riuh suara langit makin terdengar nyaring
Seakan angin malam paling berjasa
Kerlap-kerlip gemerlap cahaya lampu
Membuat layangan bak bintang bergoyang
Terombang-ambing mengikuti laju angin
Tidak ada lagi malam sunyi
Hiburan di malam di musim kemarau dimulai
Para pemuda enggan tidur
Menikmati malam di tanah lapang
Di atas hamparan sawah kering
Beramai-ramai mengajak kawan
Menerbangkan layang-layang kebanggaan
Tidak ada lagi malam sunyi
Suara nyaring layang-layang di langit tinggi
Membuat syahdu malam musim kemarau
Langit malam tak lagi sunyi sepi
Hamparan kerlap-kerlip cahaya bintang,
Layangan dan bulan membuat langit tampak asri
Ditambahi suara layangan bermelodi.
Jika kita baca, puisi itu biasa-biasa saja hanya menceritakan sebuah peristiwa bermain layang-layang di malam hari di musim kemarau, semua orang tergambar senang melakukan aktvitas itu. Penulis pun ikut merasakan kegembiraan itu, sehingga ia dapat masuk ke dalam arena kenyataan di sekitarnya, lalu kembali menghadirkannya dengan teks tulis. Puisi ini terbaca ‘jujur’ tidak memberikan kesan hiperbola, atau mengada-mengadakan perasaannya; seperti memaksa diri menghadirkan luka, rasa sedih, sepi atau bahagia ketika menulis puisi.
Lalu puisi kedua berjudul ‘Sungai Jiwa Sungai Kenangan’ karya Abdurahman Al-Hakim dari Kalimantan.
di sini memang bukan kampung kelahiran
tapi tanah perantauan
di mana masa kanak-kanak dihabiskan
dalam permainan kepolosan keluguan
keceriaan keikhlasan
angin masih membelai
kenangan kanak-kanak terurai
di antara semak dan pepohonan damai
yang mencengkeram sisi tepian sungai
sungai masih mengalirkan asa
riak-riak gelombang jiwa
bayangan permainan suatu masa
berenang dalam arus air cipta
disaksikan rumpun tumbuhan air rasa
langit masih sebiru dulu
ketika burung-burung bernyanyi rindu
dari pohon ke pohon kedamaian itu
meningkahi hari-hari yang berlalu
waktu berkabung merangkak pelan
dengan retakan kerinduan
di pundak masa lalu
yang pulang ke tanah dahulu
setelah lelah memikul beban
perjalanan perantauan
duduk kembali di tepian sungai
dengan pandangan nanar mencari damai
dalam kenangan masa lalu
yang telah layu
perihkan waktu berlalu
hingga tatapan menjadi sayu
bersandar pada sebatang pohon jiwa
yang telah kering dimakan usia
dilanda kemarau panjang polusi waktu
coba tajamkan telinga bisu
menyimak suara keceriaan itu
di antara bisingnya keangkuhan
masa depan zaman
dan suara itu telah hanyut
lenyap senyap terlarut
bersama masa lalu memagut
angan menerawang pada nafas
membaui aroma wewangian kandas
harumnya kedamaian nan lalu
tersirat dari sungai hati itu
bersama kabut mimpi pilu
pagi siang sore malam sendu
memanggil pilu perihnya kenangan itu
yang telah terluka ditoreh ambisi
lupa akan jiwa kepolosan diri
tapi di sini
jiwa kanak-kanak bumi
tetap setia menanti
pergantian hari
hingga jasad ini sepi
masa yang telah terlewati
mendesah dalam sunyi
maka di sini
masa lalu dibawa mati
Puisi ini terbaca begitu hening, sepertinya penulisnya sedang duduk di tepi sungai lalu pikirannya mengembara pada masa lalu, masa kanak-kanak, dan ia berada di tanah yang jauh dari kampung halaman, ia berada di tanah perantauan. Puisi yang panjang, tentu memiliki nafas yang panjang ketika menulisnya. Saya mengapresiasikan, ia mencoba menggunakan diksi-diksi dan bermain rima atau bunyi.
Mempertahankan keseragaman bunyi pada akhir kalimat di setiap baitnya tidak mudah dilakukan, apalagi penyair mesti memikirkan diksi yang tepat pula agar makna tidak lepas terlalu jauh dari tema yang diusung. Akan tetapi, puisi-puisi semacam ini juga memiliki banyak kelemahan untuk mencapai sebuah puisi yang estetik secara keseluruhan jika si penyair hanya mengejar rima. Sehingga puisinya akan terkesan dipaksakan.
Di puisi ketiga ‘Rintik Sembunyi’ karya Sri Aulia Dharmayanti.
Pengembaraan sederhana tentang hujan
yang rintiknya sembunyi-sembunyi
menyanyikan lagu perpisahan
mengenai jiwa-jiwa yang pergi
Sempat ia singgah pula
dengan air muka langit terdera
berguyur deras membasahi dunia
merendamnya tepat di bawah angkasa
Segala apa pun tak dapat menyembuhkan luka
yang padanya sudah ada sewadah racun
maka semua berproses sesuai jangka
yang akhirnya kembali menjadi rintik-rintik dunia
Puisi lirik, itulah yang terbaca oleh saya. Membacanya seolah sedang bermain gitar atau bernyanyi. Ia menceritakan tentang hujan yang jatuh ke bumi dengan berbagai maknanya yang didapatkan oleh mereka yang terkena rintik-rintiknya. Puisi yang menghadirkan hikmah dengan lirik dari bait-bait.
Itulah yang terbaca dari puisi-puisi yang datang ke meja kerja saya. Tentu saja bukan berarti puisi-puisi lainya terkesan buruk atau jelek. Berproseslah dengan gembira dalam menulis puisi, semua akan indah pada waktunya dan karya-karya Anda akan mencapai titik puncak pencapaiannya.
Selamat Berkarya.
Oktober 2023
[1] Peraih Penghargaan Acarya Sastra IV Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Kemendikbud RI tahun 2015